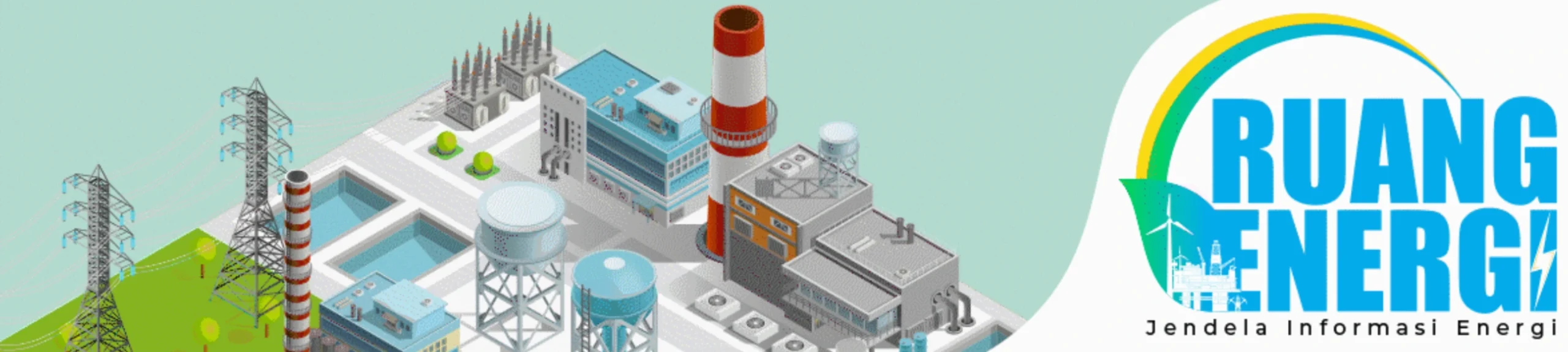Jakarta, ruangenergi.com- Dunia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menyediakan energi yang bersih, terjangkau, dan berkelanjutan. Pengembangan energi terbarukan (EBT) seperti matahari, angin, air, dan panas bumi adalah langkah solutif untuk menjawab tantangan tersebut.
Namun pengembangannya juga tak mudah. Minimnya ketersediaan infrastruktur, teknologi dan kebutuhan dana investasi yang relatif lebih besar ketimbang energi fosil, kerap menjadi batu sandungan dalam mengakselerasi pengembangan EBT terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
“Karenanya, perlu komitment yang kuat dari pemerintah dan para stakeholders terkait sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM),” kata Komaidi Notonegoro, Pengamat Energi dari Reforminer Institute, di sela-sela EITS DISCUSSION SERIES 2024: “Transformasi Hijau Menuju Masa Depan Energi yang Lebih Bersih dan Berkelanjutan” yang digelar di Ballroom Brass Thamrin Nine, Rabu (05/06/2024), di Jakarta.
Gelaran diskusi ini disajikan oleh Energi Institute for Transition (EITS) bekerjsama dengan Oksmedia Group – konsultan media dan event organizer, sebagai upaya bersama dalam mengakselerasi transformasi bisnis sektor ESDM menuju masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Komaidi menambahkan, transisi energi ini sangat baik, namun disayangkan analisisnya sering kali hanya berhenti pada aspek lingkungan saja.
“Tapi, setelah itu kita masuk ke aspek UUD alias ujung-ujungnya duit, bisa beli atau tidak, itu sering kali berhenti,” tegasnya.
Bicara EBT, menurutnya, ketika sudah bersentuhan dengan daya beli, inflasi, akan terhenti. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara maju. Dia mencontohkan, saat awal perang Rusia-Ukraina, Inggris dan Jerman kembali menyalahkan PLTU mereka lantaran sanksi yang mereka berikan terhadap Rusia.
Kala itu, Rusia memberi sanksi balik, dengan mengurangi alokasi atau menghentikan pasokan gas di saat masyarakat kedua negara tak lagi bicara soal lingkungan tetapi kehidupan secara menyeluruh.
“Kalo listirk naik 10 kali lipat dibanding tarif normal, apa yang terjadi? Yang tejadi adalah resiko ekonomi dan sosial. Karena itu kita harus hati-hati. Saya sampaikan ini bukan untuk pesimis, tetapi perlu bijaksana, kita perlu helicopter view yang lebih tinggi melihat petanya lebih luas lagi,” jelasnya.
Data dari Reformainer Institute menyebutkan, jika semua minyak dan batu bara dikonversi menggunakan gas, penurunan emisinya setera dengan target penurunan emisi di sector energy tahun 2030 sebesar 314 juta ton.
“Kalau itu semua dikonfersi, sudah sampai angka 319 juta ton. Artinya lebih besar dari target di sektor energi,” paparnya.
Jika bicara NZE, itu artinya semua sektor, tapi dia justru mempertanyakan, sebab kenyataannya Indonesia hanya fokus pada transisi energi. Kemudian, jika bicara data, dari tahun 2000 – 2022 emisi yang dihasilkan sektor energi di Tanah Air hanya 18 persen.
“Artinya 82 persen dihasilkan oleh non sektor energi. Nah, bila kita hanya fokus pada prosentase itu maka NZE tidak akan tercapai,” ujarnya.
Komaidi juga mengungkapkan keungulan sumber energy terbarukan panas bumi. Menurutnya panas bumi merupakan EBT dengan sumber yang tidak terbatas dan tidak tergantung dengan cuaca sehingga sangat dapat diandalkan untuk jangka panjang.
“Kita bicara EBT apapun, energy air akan terganggu di musim kemarau, energy surya akan tergangu saat musim hujan, sedang angin juga debitnya tidak sama, artinya tergantung cuaca,” jelasnya.