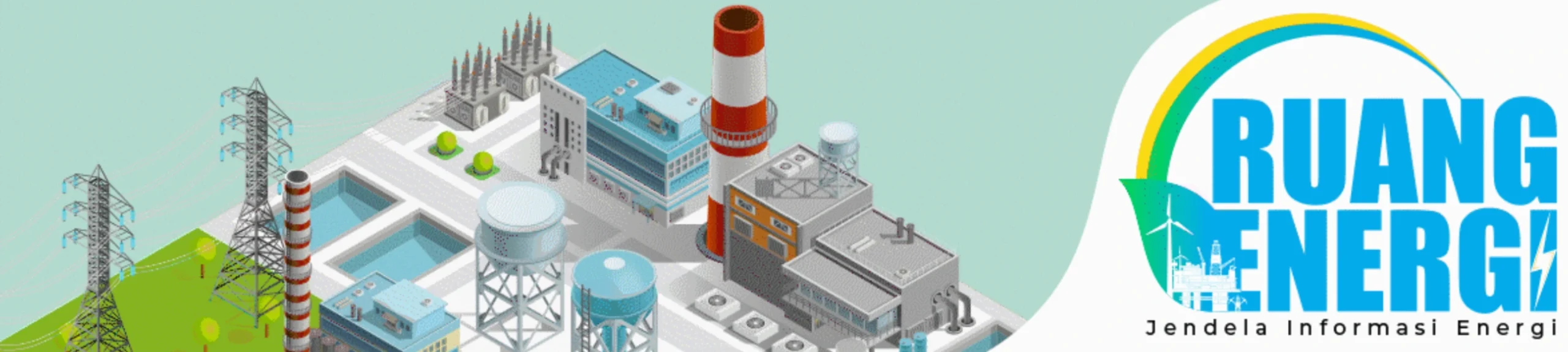Jakarta, ruangenergi.com- Transisi menuju energi hijau telah menjadi wacana global dalam beberapa dekade terakhir, termasuk di Indonesia. Green financing atau pembiayaan hijau muncul sebagai instrumen penting dalam mendukung pengembangan energi terbarukan.
Namun, di antara optimisme yang digaungkan, kenyataan di lapangan menunjukkan berbagai tantangan yang belum terselesaikan. Artikel ini mengupas realitas transisi energi hijau di Indonesia, termasuk hambatan, peluang, dan usulan solusi realistis.
Komitmen Energi Hijau: Optimisme atau Janji?
Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Namun, faktanya, hingga 2024, kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi primer baru mencapai sekitar 12%. Target ini pun telah diubah menjadi net zero emission pada tahun 2060, dengan memasukkan energi nuklir sebagai opsi. Perubahan dan moving target ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan energi nasional.
Sumber daya alam utama Indonesia adalah batubara, yang menyumbang sekitar 67% kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia (dari total sekitar 93.000 MW). Dengan keunggulan biaya produksi dan stabilitas pasokan, batubara tetap menjadi andalan dalam sistem ketenagalistrikan nasional.
Mengingat hal ini, menutup PLTU batu bara sepenuhnya pada tahun 2050 atau 2060 tampaknya kurang realistis.
Hambatan Regulasi dan Implementasi
Regulasi yang tidak konsisten dan minimnya insentif menjadi penghambat utama investasi energi hijau. Beberapa fakta di lapangan meliputi:
• Kemudahan Perizinan: Proses perizinan proyek energi hijau sering kali rumit dan memakan waktu, meskipun pemerintah telah menjanjikan kemudahan.
• Insentif Pajak: Hingga saat ini, pengurangan pajak untuk proyek energi terbarukan masih sebatas wacana.
• Kegagalan Proyek Besar: Program 35.000 MW yang dicanangkan pada era Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagian besar terdiri dari PLTU batu bara. Hingga kini, banyak proyek yang tidak jelas kelanjutannya.
Selain itu, skema internasional seperti Indonesia Energy Transition Mechanism (IETM) yang dijanjikan di forum G20 Bali yang lalu, dengan komitmen pendanaan sebesar USD 1,26 miliar, belum memberikan hasil konkret.
Kendala seperti birokrasi yang berbelit, persyaratan donor yang rumit, dan perubahan politik global, termasuk kembalinya Donald Trump sebagai Presiden AS, ditengarai menghambat progres ini. Kita belum lupa pada masa kepemimpinan sebelumnya (Trump 1.0) Amerika Serikat menarik diri dari Paris Agreement yang sangat peduli untuk mengekang emisi gas rumah kaca.
Menteri Energi yang sekarang ditunjuk pada periode Trump 2.0 adalah mantan pengusaha energi fosil, yang kemungkinan besar memiliki pandangan pro fosil. Dinamika global seperti ini tentu tidak dapat diabaikan.
Ketergantungan pada Batubara dan Tantangan Geothermal
Batubara merupakan salah satu sumber daya alam utama Indonesia, dengan cadangan melimpah dan biaya produksi yang kompetitif. Dari sisi stabilitas energi, batubara masih menjadi pilihan utama bagi PT PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional. Ini menimbulkan dilema: transisi energi hijau harus dilakukan, tetapi mengabaikan potensi batubara dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan ketahanan energi.
Di sisi lain, geothermal memiliki potensi besar, dengan cadangan mencapai 28,5 GW, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan potensi terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 2,3 GW. Beberapa hambatan utama meliputi:
• LCOE (Levelized Cost of Energy): Geothermal sering kali dianggap mahal dibandingkan batubara.
• Dominasi PLN: Pengembang geothermal tidak dapat menjual listriknya langsung kepada konsumen, termasuk melalui mekanisme power wheeling. Dominasi ini diperkuat oleh interpretasi konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait posisi PLN.
Tantangan dalam Pengembangan Energi Terbarukan
Selain kendala institusionalitas dan interpretasi konstitusi di atas, faktor faktor seperti biaya investasi yang tinggi, regulasi yang kompleks dan risiko eksplorasi juga tinggi
• Wacana insentif untuk energi terbarukan, masih lebih merupakan retorika yang mengurangi minat investasi
• Ketergantungan kepada batubara adalah keniscayaan saat ini. Batubara tetap merupakan andalan karena ketersediaan, biaya produksi yang rendah serta kestabilan daya. Dengan demikian, transisi ke energi terbarukan merupakan tantangan tersendiri, tidak seperti di negara lain yang teknologi maupun kekayaan alam geografisnya lebih mendukung ke energi terbarukan
Mekanisme Kredit Karbon dalam Skema CDM
Skema Clean Development Mechanism (CDM) menawarkan peluang pembiayaan proyek hijau dengan insentif kredit karbon. Namun, manfaat utama dari skema ini sering kali dinikmati oleh negara donor, bukan negara penerima seperti Indonesia. Dalam mekanisme ini:
• Negara donor yang mendanai proyek mendapatkan kredit karbon yang dapat digunakan untuk memenuhi target emisi mereka.
• Negara penerima hanya mendapatkan manfaat sekunder, seperti pengurangan emisi lokal dan transfer teknologi.
Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme CDM perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat lebih besar bagi negara penerima, terutama dalam hal pendanaan dan pengakuan karbon kredit. Komitmen Negara maju maupun lembaga internasional seperti UNFCCC diperlukan dalam hal ini. Kita menggunakan dan hidup di dunia yang sama.
Peran Perbankan dan Legal Lending Limit
Perbankan domestik memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan hijau. Namun, beberapa kendala berikut menghambat kontribusinya:
• Legal Lending Limit (LLL): Ketentuan ini membatasi jumlah kredit yang dapat diberikan bank kepada sektor tertentu untuk menjaga rasio kecukupan modal.
• Risiko Tinggi: Proyek energi terbarukan dianggap memiliki risiko tinggi oleh perbankan karena ketidakpastian regulasi dan ketergantungan pada skema internasional seperti CDM.
Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan insentif pemerintah berupa jaminan risiko atau pembentukan dana garansi hijau.
Usulan Solusi Realistis
1. Optimalisasi Sumber Daya yang ada: Batubara masih menjadi andalan, Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaannya dilakukan dengan teknologi yang ramah lingkungan, sperti penerapan teknologi clean coal
2. Regulasi yang Konsisten dan Tegas:
• Pemerintah perlu menetapkan insentif pajak yang konkret dan memastikan implementasinya.
• Penyederhanaan proses perizinan dengan digitalisasi dan integrasi antar lembaga.
3. Optimalisasi Geothermal:
• Berikan subsidi atau skema risiko bersama untuk mendukung eksplorasi awal.
• Dorong PLN untuk meningkatkan absorpsi energi geothermal dengan memberikan harga pembelian yang kompetitif.
4. Pengembangan Skema Pendanaan Baru:
• Pendirian dana garansi hijau untuk mengurangi risiko bagi sektor perbankan.
• Perluasan pasar karbon domestik untuk menciptakan insentif ekonomi bagi proyek hijau.
5. Transisi Bertahap yang Realistis:
• Fokus pada hibridisasi pembangkit energi dengan mengintegrasikan sumber terbarukan seperti surya ke dalam PLTU yang sudah ada.
• Prioritaskan pengurangan emisi secara bertahap daripada berfokus pada target yang sulit dicapai.
6. Kerja Sama Internasional yang Efektif:
• Tingkatkan negosiasi untuk mendapatkan syarat yang lebih sederhana dari donor internasional.
• Harmonisasi regulasi energi hijau dengan standar internasional untuk meningkatkan daya tarik investasi.
Penutup
Green financing adalah kebutuhan mendesak untuk mendukung transisi energi hijau di Indonesia. Namun, optimisme harus disertai dengan langkah-langkah realistis dan implementasi konkret.
Pemerintah dan pemangku kepentingan harus mengutamakan stabilitas ekonomi dan energi dalam setiap kebijakan yang diambil. Pendekatan realistis dan pragmatis itu perlu. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan transisi energi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Talk is cheap, tetapi langkah nyata adalah kuncinya.
Terima kasih – Januari 2025

Penulis Sampe L.Purba, Lulusan Universitas Pertahanan RI bidang Geostrategi Energi, Alumni PPRA Lemhannas dan Staf Ahli Menteri ESDM 2019-2023