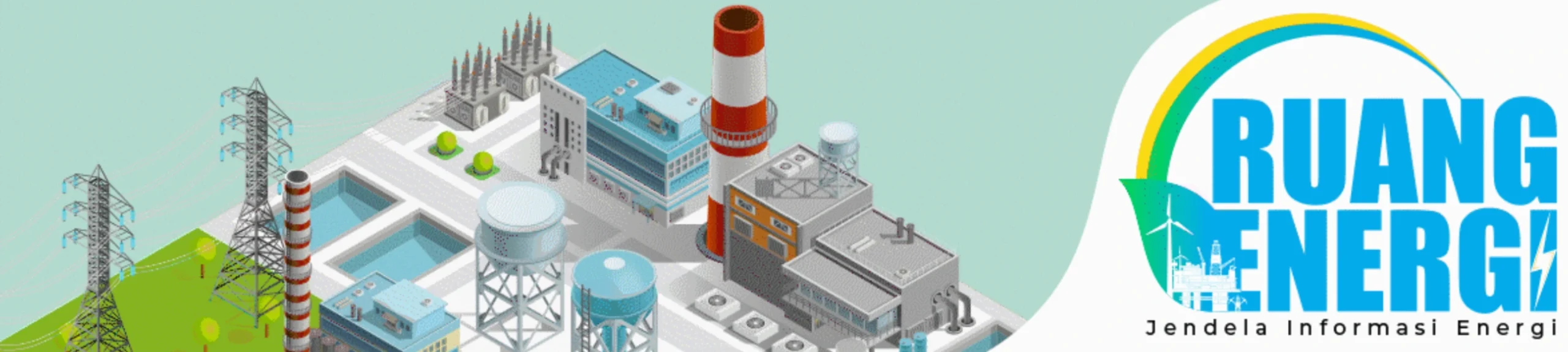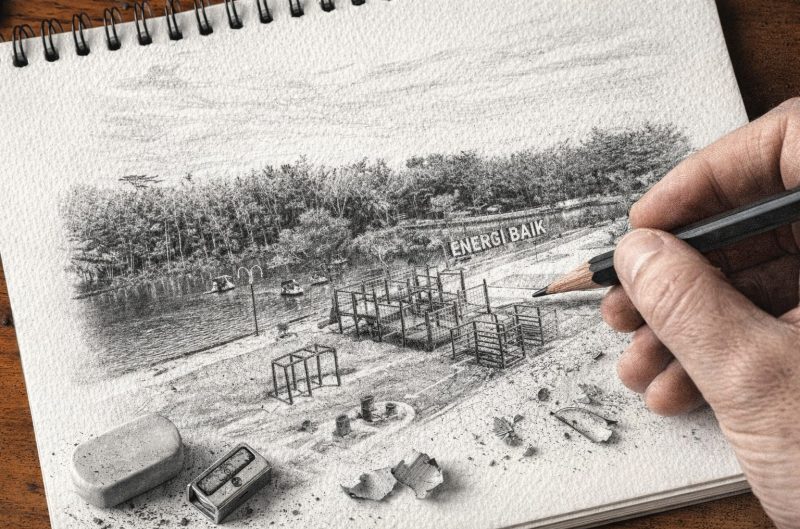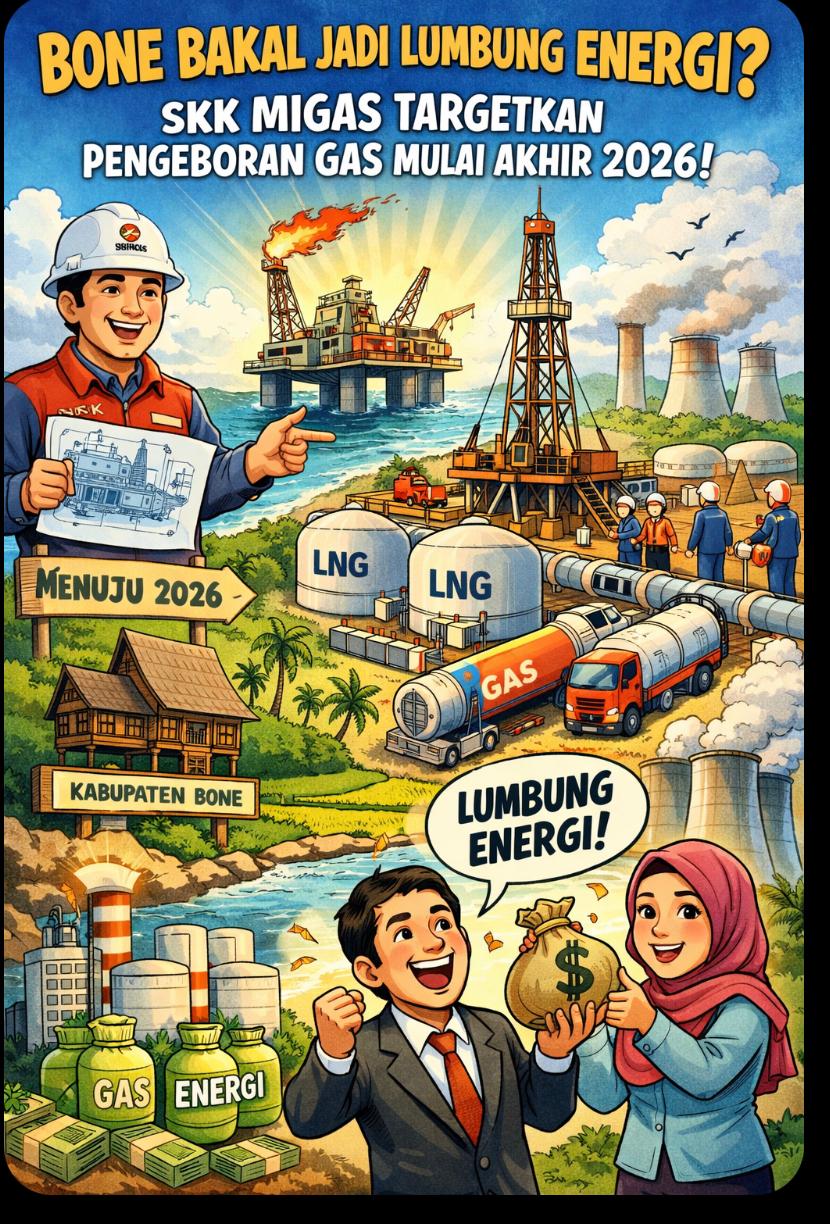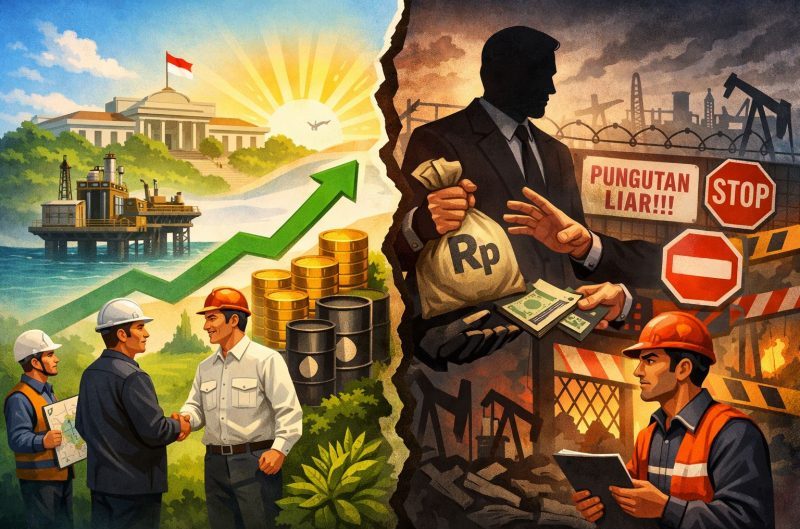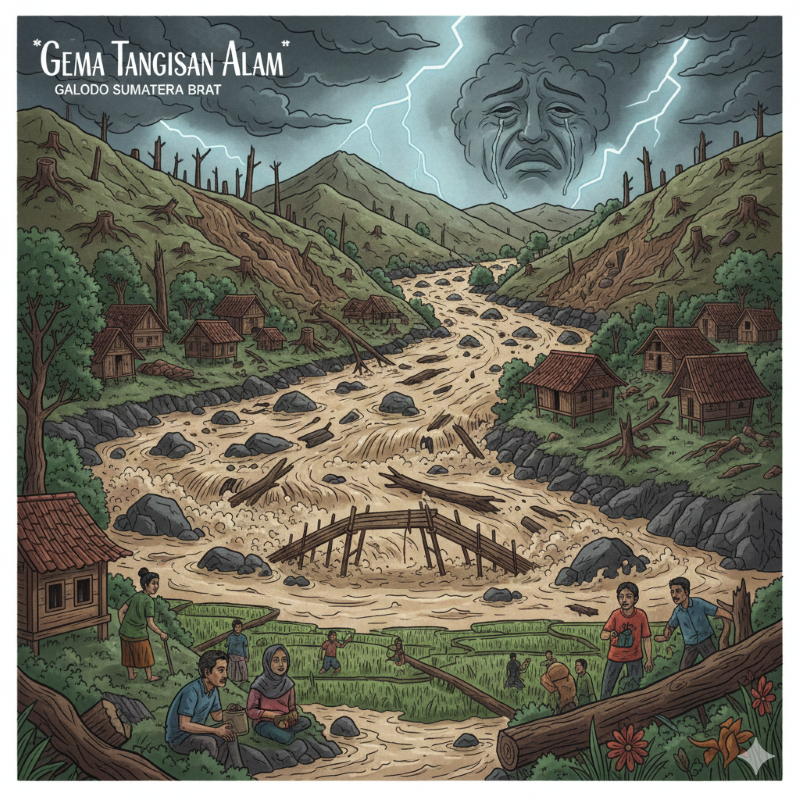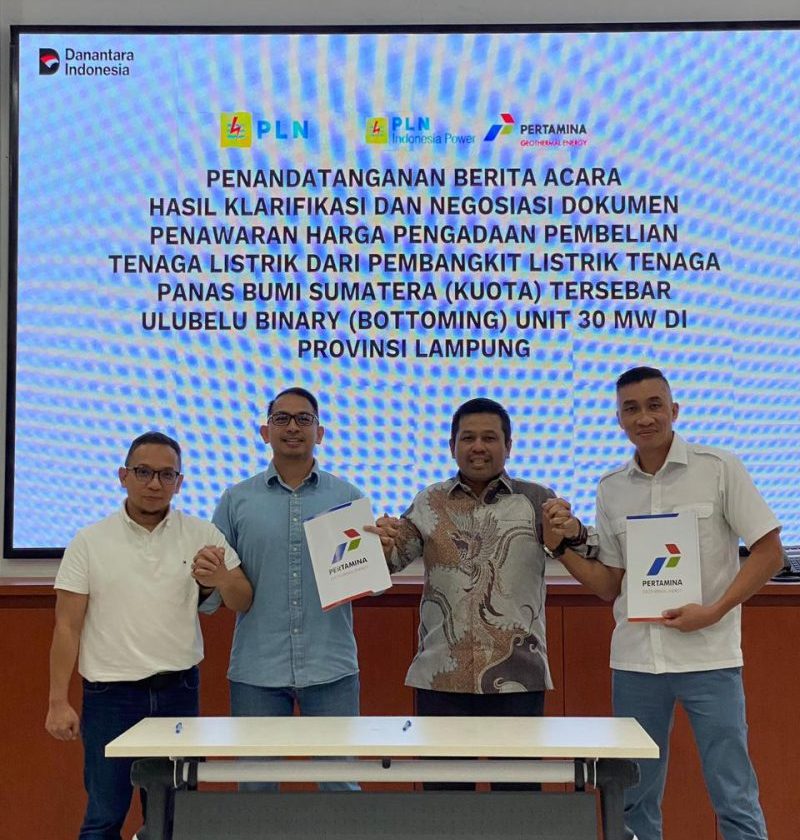Jakarta, ruangenergi.com – Di tengah eskalasi konflik Iran–Israel yang terbaru, dunia kembali menoleh pada simpul vital bernama Selat Hormuz. Dalam teater geopolitik 2025, kawasan ini menjadi arena terbuka setelah serangan presisi militer Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran—Fordow, Natanz, dan Isfahan. Apa yang semula tampak sebagai respons taktis kini menjelma menjadi babak baru kontestasi kekuatan global. Selat Hormuz bukan lagi sekadar jalur maritim; ia adalah titik pertemuan antara strategi energi, supremasi militer, dan redefinisi kemitraan dunia.
Geografi Strategis dan Ketentuan Hukum Laut
Secara letak, Selat Hormuz merupakan muara dari Persian Gulf Sea—sebuah perairan tertutup yang dikelilingi oleh negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UEA, Bahrain, dan Irak. Keseluruhan ekspor energi mereka, termasuk minyak dan gas, hanya memiliki satu pintu keluar: Selat Hormuz.
Selat ini membentang sekitar 154 km, dengan lebar tersempit sekitar 33 km, diapit oleh Iran dan Oman. Zona teritorial 12 mil laut dari masing-masing sisi menyebabkan tumpang tindih yurisdiksi dan minimnya ruang laut bebas (high seas). Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 38 dan 44, Hormuz dikategorikan sebagai selat internasional yang tunduk pada prinsip transit passage—yang tidak bisa dibatasi bahkan dalam masa konflik bersenjata.
Ketergantungan Ekonomi dan Energi Global
Setiap hari, ±20,5 juta barel minyak melewati Hormuz—sekitar 30% dari perdagangan minyak laut dunia. Qatar menyalurkan 100% ekspor LNG-nya melalui jalur ini, menjadikannya ±20% dari pasar LNG global. Negara-negara seperti Arab Saudi, Irak, dan UEA juga sangat menggantungkan dirinya pada selat ini untuk ekspor energi mereka.
Sebanyak 84% pengiriman energi dari Hormuz menuju Asia, khususnya China, India, Jepang, dan Korea Selatan. Fakta ini menjadikan Selat Hormuz bukan hanya urat nadi Timur Tengah, tetapi denyut jantung sistem energi global.
Chokepoint Global dan Operasi Maritim
Kerapuhan kawasan ini sudah teruji dari Perang Tanker dekade 1980-an hingga insiden penyitaan kapal 2019. Dalam konflik terbaru, Amerika Serikat kembali mengaktifkan Operasi Sentinel, sebuah koalisi maritim multinasional yang bertugas menjaga kebebasan navigasi di Selat Hormuz, Teluk Oman, dan Bab el-Mandeb. Operasi ini melibatkan patroli udara, kapal pengawal, serta sistem radar terintegrasi yang mendeteksi potensi gangguan seperti ranjau laut, pembajakan, atau sabotase logistik.
Serangan ke Fasilitas Nuklir dan Manuver Iran
Serangan udara AS pada Juni 2025 terhadap fasilitas Iran—Fordow yang terkubur dalam pegunungan, Natanz sebagai pusat pengayaan uranium utama, dan Isfahan yang menjadi lokasi konversi bahan bakar nuklir—mengindikasikan eskalasi yang melampaui diplomasi. Iran menanggapi dengan ancaman menutup Hormuz sebagai bentuk preemptive strategic deterrence, meskipun secara hukum laut tindakan tersebut melanggar prinsip freedom of navigation.
Kehadiran Aktor Global: Antara Kepentingan dan Kalkulasi
Konflik ini tidak lepas dari figur-figur kunci dunia: Ayatollah Ali Khamenei yang memegang supremasi spiritual dan strategis Iran; Benjamin Netanyahu dengan postur pertahanan Israel yang cenderung pre-emptive; Donald Trump yang mewariskan doktrin tekanan maksimum; hingga Vladimir Putin dan Xi Jinping, yang memainkan langkah sabar namun penuh makna dalam peta geopolitik global. Masing-masing tokoh ini mewakili lebih dari negaranya—mereka adalah personifikasi dari kepentingan energi, keamanan teknologi militer, dan penataan ulang aliansi dunia.
Lebensraum dan Ekspansi Strategis
Dalam kerangka lebensraum, negara besar seperti Iran, AS, dan Rusia bergerak laksana organisme strategis: butuh ruang untuk bernapas, mengakses logistik, dan membangun pengaruh. Konsep Großraumordnung Carl Schmitt menyebutnya sebagai ruang tatanan besar di mana hukum dominan tidak lagi nasional, melainkan hegemonik. Hormuz saat ini menjadi panggung kompetisi pengaruh dari kekuatan besar—masing-masing membawa koalisi, doktrin, dan demonstrasi militer mutakhir.
Polarisasi Regional dan Ketegangan Mazhab
Negara-negara Teluk menghadapi dilema antara netralitas, keterikatan ekonomi dengan Barat, dan tekanan ideologis dari Iran. Meski Iran menggunakan narasi pembelaan terhadap Palestina, relasi mazhab Syiah–Sunni tetap menjadi sumber kecurigaan. Serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran justru memperkuat persepsi bahwa Iran menjadi sasaran kolektif dari blok Barat, memaksa negara-negara Teluk mempertimbangkan ulang postur keamanan dan hubungan eksternalnya.
Sikap Rusia, RRC, India, dan Pakistan: Kekhawatiran Terkendali
Negara-negara seperti Rusia dan RRC akan menyuarakan keprihatinan strategis, namun sangat berhati-hati agar tidak terseret ke dalam eskalasi militer langsung. India akan fokus pada stabilitas suplai energi, sementara Pakistan—meski memiliki kedekatan budaya dan sektarian dengan Iran—juga akan menimbang relasinya dengan negara Teluk dan China.
Tapi penting dicatat: meski skala konfliknya besar dan multiaktor, kemungkinan perang dunia tetap kecil, justru karena kalkulasi strategis semua pihak yang lebih mengedepankan penataan ulang pengaruh ketimbang konflik total.
Reposisi Amerika Serikat dan Revisi Kemitraan
Seiring meningkatnya tekanan di Indo-Pasifik dan Eropa Timur, AS mungkin melakukan recalibration of strategic alliances. Hubungan historis dengan Israel bisa mengalami penyesuaian jika langkah Tel Aviv dianggap mengganggu keseimbangan kawasan. Pandangan realis Lord Palmerston kembali relevan: “No eternal allies, no perpetual enemies. Only interests are eternal.”
Artinya, negara-negara Teluk maupun Iran harus membaca ulang isyarat geopolitik Washington—bukan sebagai soal loyalitas, tapi soal relevansi dalam peta kekuatan global yang tengah direstrukturisasi.
Posisi Indonesia: Bijak, Aktif, dan Tidak Terseret Retorika
Sebagai negara dengan prinsip bebas aktif, Indonesia harus tetap berpijak pada kepentingan nasional, bukan pada tarik-menarik blok ideologis atau tekanan emosional yang berkelindan di media sosial. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk tidak menyeret isu agama ke ruang publik secara reaktif—karena konflik ini bukan semata benturan keyakinan, melainkan pertempuran pengaruh, strategi persenjataan, dan pemosisian ulang tata dunia.
Indonesia perlu tetap waspada, cerdas dalam diplomasi, dan bersuara berdasarkan kalkulasi rasional, bukan sentimen. Hormuz 2025 adalah arena ujian bagi dunia, dan juga cermin bagi keteguhan Indonesia sebagai kekuatan regional yang berdaulat.
oleh Sampe L. Purba