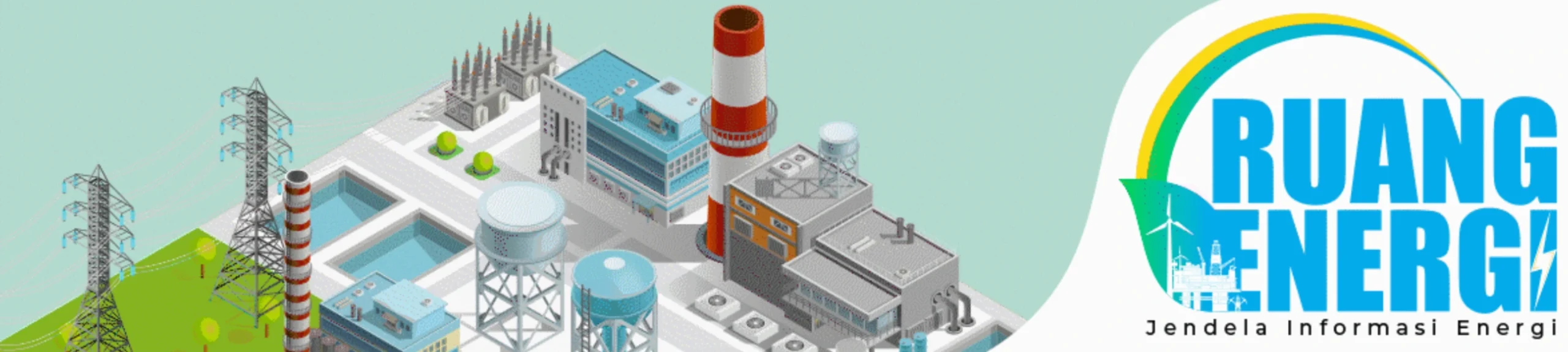Jakarta, Ruangenergi.com – Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja alias Omnibus Law, telah diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan resmi untuk diundangkan.
Menurut, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI periode 2017-2019, Inas Nasrullah Zubir, UU Cipta Kerja yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi kemudian dipersoalkan. Di mana salah satunya adalah paragraf 5, pasal 40 UU Cipta Kerja yang memuat tentang perubahan UU No. 22/2001, pasal 1, ayat 3 yang berbunyi:
“Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi” katanya saat dihubungi Ruangenergi.com, (04/11).
“Lalu apa yang dipersoalkan dari klausal tersebut? Padahal frasa (Minyak dan Gas Bumi) adalah teknik penulisan dalam penyusunan rancangan undang-undang untuk mendefinisikan frasa (Minyak Bumi dan Gas Bumi) agar lebih singkat menjadi (Minyak dan Gas Bumi), yang banyak digunakan dalam RUU Cipta Kerja klaster ESDM maupun UU Migas No. 22 tahun 2001,” sambungnya.
Ia menjelaskan, Gas bumi dalam ketentuan pasal 1, ayat 2 sudah di definisikan, sedangkan minyak tidak ada definisinya di ketentuan, akibatnya akan bias, karena minyak saja dapat diartikan minyak bumi, minyak solar, minyak tanah dan lain-lain.
“Oleh karena itu, frasa (Minyak dan Gas Bumi) harus didefinisikan didalam kententuan, agar tidak biasa dan tetap diartikan sebagai minyak bumi dan gas bumi,” jelas Inas.
Selain itu, lanjutnya, dalam outlook tahunan OPEC yang memperkirakan konsumsi minyak dunia tumbuh 7,3 juta bph dari periode 2017 sampai 2023. Di mana perkiraan menyentuh 104.5 juta barel di 2023, akan tetapi setelah itu pertumbuhan permintaan akan melambat hingga tahun 2040.
“Terjun bebasnya harga minyak sejak awal Pandemi Covid-19, semakin mempengaruhi percepatan dari melambatnya pertumbuhan permintaan minyak dunia, dan tentunya akan mempengaruhi kinerja investor kedepan-nya,” tuturnya.
Ia melanjutkan, UU Cipta Kerja memang membuka kemudahan berinvestasi di sektor migas, tapi jangan lupa kondisi geografi Indonesia juga mempengaruhi minat investasi migas di Indonesia, apalagi cadangan proven (terbukti) tinggal sekitar 3.2 milyar barel saja.
“Persoalan energi Indonesia memang menjadi perhatian pemerintah, sehingga batubara juga menjadi pilihan untuk diolah,” imbuhnya.
Untuk itu, Pemerintah menyiapkan roadmap percepatan peningkatan nilai tambah batubara dengan cara mengoptimalisasikan pemanfaatan batu bara dalam negeri, melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan.
“Nah, salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah tersebut adalah melalui gasifikasi batubara menjadi syngas atau synthetic gas yang diperlukan untuk industri petrokimia, serta dimethyl ether (DME) gas sebagai substitusi LPG,” beber Inas.
“Kenapa LPG harus di substitusi? Karena import LPG setiap tahun-nya naik terus, dan berdasarkan data tahun 2019 saja, yang di import sebanyak 75 persen dari konsumsi nasional atau setara dengan 5.73 juta ton LPG,” terangnya kembali.
Lebih jauh, ia mengatakan, sekarang ini ada 2 BUMN yang mendapat tugas dari pemerintah untuk membangun kilang gasifikasi batubara tersebut.
Adalah Pertamina yang akan bekerjasama dengan perusahaan pertambangan, dengan kapasitas 2 juta ton per tahun serta PTBA (Bukit Asam), dengan kapasitas 1.4 juta ton per tahun, dimana nilai investasi PTBA adalah 2.4 miliar dolar.
“Sehingga insentif batubara dalam bentuk royalti nol persen yang kemudian ditentukan dalam pasal 128A UU Cipta Kerja, gunanya untuk memacu industri gasifikasi batubara tersebut agar segera terealisasi dan tidak hanya melulu menjual batubara dalam keadaan mentah, melainkan menjualnya dalam bentuk produk jadi lain-nya,” tandas Inas.