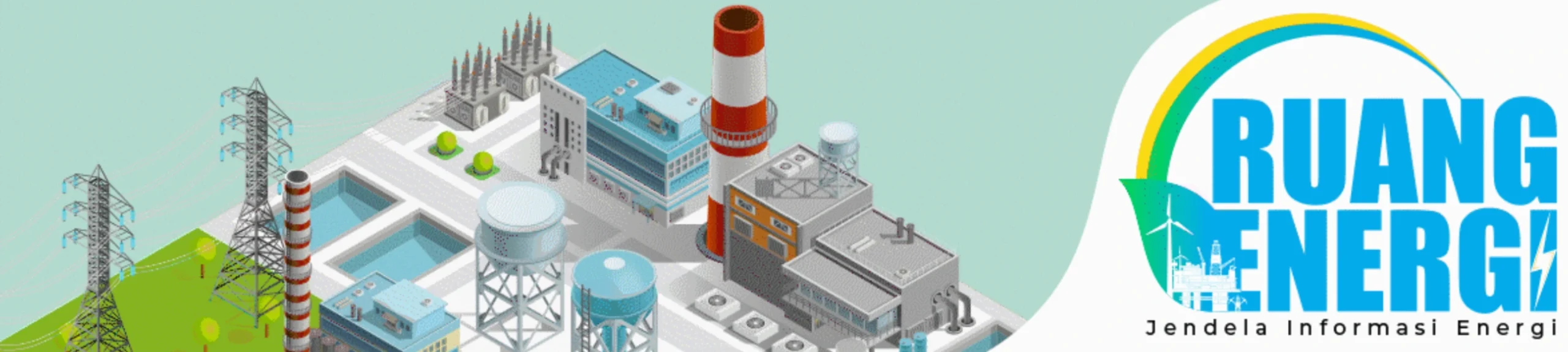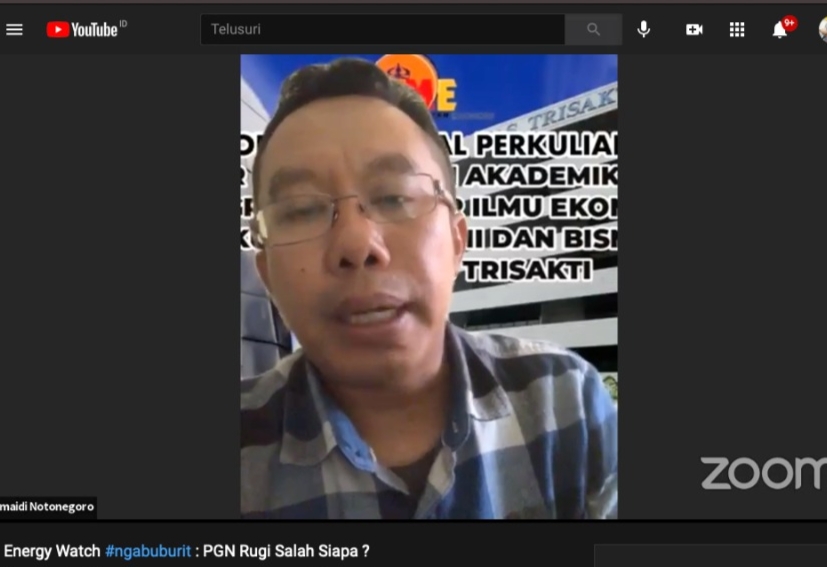Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, bisnis yang dijalankan oleh PT PGN Tbk, sebenarnya bisnis midstream seperti bisnis jalan tol.
Dalam diskusi online yang digelar Energy Watch bersama Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) dan Situs Energi bertemakan “PGN Rugi Salah Siapa?”, yang disiarkan melalui channel YouTube Ruang Energi, Jumat (16/04), Komaidi menambahkan, ada dua yang dilakukan oleh PGN.
Pertama bisnis transmisi dan distribusi gas bumi, yang mana PGN mengambil toll fee dari setiap mmbtu gas yang melewati atau menggunakan infrastrukturnya, dan tarifnya sudah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Kedua, yang dilakukan PGN adalah bisnis niaga gas, seperti lembaga intermediasi kalau di perbankan.
“Membeli dari hulu berapa kemudian di jual ke hilir berapa, selisihnya lah yang diambil oleh PGN,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan di tahun 2016 lalu, dengan adanya masukan dari Kamar Dagang Industri (Kadin) dan dari pengusaha mengenai daya saing di sektor industri. Akhirnya pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, dan kemudian direvisi melalui Perpres nomor 121 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Lalu, di tahun yang sama terbit juga Peraturan Menteri ESDM nomor 40 tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi Untuk Industri Tertentu. Kemudian, Kepmen ESDM nomor 89 K/10/MEM/2020 dan Kepmen ESDM nomor 91K/10/MEM/2020 terkait Harga dan Pengguna Gas Bumi di Bidang Industri dan Kelistrikan.
“Disana di patok maksimal US$ 6 per mmbtu di plant gate, artinya dititik serah pengguna. Jadi kalau industri keramik berarti sampai di sana (industri keramik) maksimal harga gas sebesar US$ 6 mmbtu,” ungkap Komaidi.
“Saya kira ini (harga gas US$ 6) yang menjadi problem sejak awal regulasi ini diterbitkan, dan kami sudah mengkritisi hal tersebut. Kalau kita lihat sebaran harga gas di kepala sumur (well head) atau di hulunya, untuk Indonesia bagian barat rata-rata sudah diatas US$ 7 bahkan ada yang US$ 9 atau pula yang sudah US$ 10 per mmbtu,” urai Komaidi.
“Menurut saya ini sebetulnya tidak cukup logis, karena harga di well head berkisar US$ 7 – US$ 10 per mmbtu, akan tetapi PGN menjualnya sebesar US$ 6 per mmbtu. Jangankan untung, biaya transportasinya saja sudah tidak ketemu,” imbuhnya.
Ia menyarankan untuk mengeceknya langsung dari KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Untuk di wilayah Indonesia bagian barat, katanya, itu cost of production-nya sudah diatas US$ 6, otomatis mereka menjual diatas US$ 7 per mmbtu.
“Saya kira PGN beli seperti itu, kalau beli (gas) sebesar US$ 7 per mmbtu, lalu menjualnya dengan harga US$ 6 per mmbtu tidak ketemu rumusnya. Saya kira mereka (PGN) melakukan berbagai upaya untuk melakukan subsidi silang, misalnya membeli dari wilayah Indonesia timur di kisaran US$ 2 – US$ 4 per mmbtu,” bebernya.
Yang menjadi permasalahan disini adalah industri gas ini, kata Komaidi, antara sebaran produksinya atau penggunanya berbeda-beda. Bisa dikatakan sebanyak 85% cadangan dan produksi gas ada di wilayah Indonesia timur, namun demikian 85% penggunanya berada di wilayah Indonesia bagian barat.
“Mau tidak mau infrastruktur menjadi kunci untuk mensuplai atau memberi pasokan gas ke end user,” imbuhnya.
“Menurut saya selain sengketa pajak, masalah harga gas yang di patok menjadi US$ 6 per mmbtu ini menjadi akar permasalahan,” jelas Komaidi.
“Saya kira bukan hanya PGN tetapi hampir semua rantai bisnis di gas, hanya saja yang sudah kena dan teriak duluan PGN. Saya kira hampir mati bareng-bareng rantai bisnis di gas, coba tanya ke Medco, Pertamina, Pertagas yang jualan gas, saya kira sama saja. Hanya saja magnitude nya karena PGN ini bisnisnya banyak di niaga maka mereka yang terpukul lebih banyak,” tandas Komaidi.