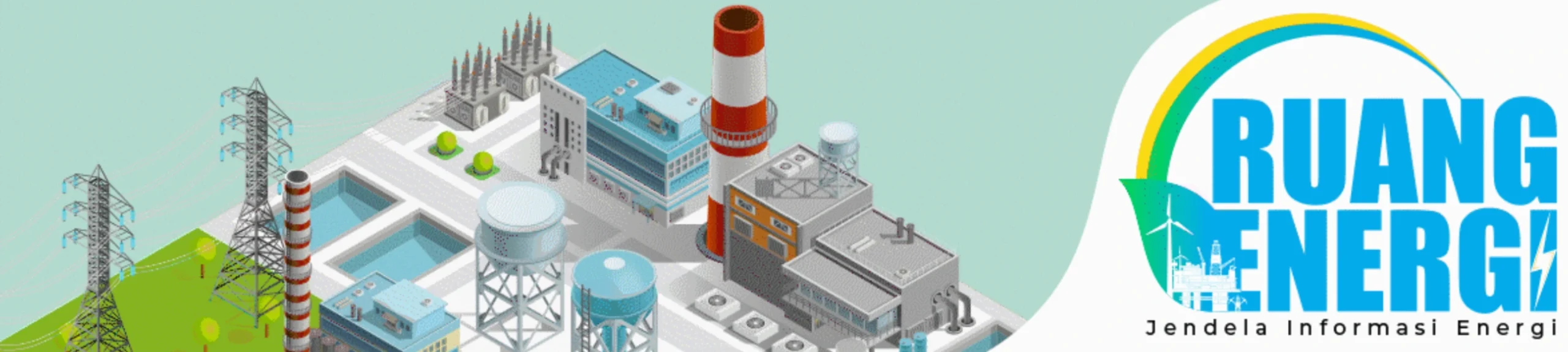Jakarta Pusat, Jakarta, ruangenergi.com-Prestasi gemilang ditorehkan oleh Yosef Hilarius Timu Pera. Akademisi ini resmi dikukuhkan sebagai Doktor Sosiologi ke-141 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) dengan predikat summa cumlaude alias nilai sempurna, IPK 4.00.
Namun, di balik angka sempurna tersebut, disertasinya menawarkan temuan yang jauh lebih berharga: sebuah bedah anatomi mendalam mengenai praktik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) di tanah Papua.
Lewat disertasi berjudul “Bauran Praktik CSR Perusahaan Migas Multinasional di Papua Barat: Studi Kasus Tangguh Sustainable Development Plan (TSDP) BP Tangguh (2015–2020)”, Yosef menyoroti bagaimana raksasa migas menavigasi risiko di wilayah yang kaya sumber daya namun rentan konflik,seperti dikutip dari website FISIP UI.
Bukan Sekadar Amal, Tapi Tameng Risiko
Dalam paparannya, Yosef menegaskan bahwa bagi perusahaan migas, CSR bukan sekadar bagi-bagi bantuan sosial. Urgensinya jauh lebih besar dibandingkan industri lain. Mengambil contoh bencana lingkungan global seperti tumpahan minyak Exxon Valdez (1989) dan Deepwater Horizon (2010), Yosef mengingatkan bahwa risiko operasional migas bisa merusak ekosistem dan memicu kemarahan publik.
Terlebih, proyek migas kerap beroperasi di wilayah dengan dinamika sosial-politik tinggi, yang rentan terhadap konflik sumber daya dan isu hak asasi masyarakat lokal.
“Oleh karena itu, CSR di sektor migas tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memitigasi risiko, menjaga legitimasi bisnis, dan mendukung keberlanjutan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasi,” jelas Yosef.
Tarik Ulur Kepentingan: Global vs Lokal
Melalui riset kualitatif yang melibatkan wawancara mendalam dengan 47 informan kunci dan survei terhadap 315 responden masyarakat kampung di Teluk Bintuni, Yosef menemukan adanya “pertarungan” kepentingan.
Praktik CSR di Indonesia, menurutnya, dipengaruhi tiga lapisan:
-
Faktor Global: Standar keberlanjutan internasional.
-
Faktor Nasional: Regulasi pemerintah (AMDAL, SKK Migas).
-
Faktor Lokal: Tuntutan masyarakat adat dan pemerintah daerah yang sangat dinamis.
Dalam kasus BP Tangguh, terjadi dialektika antara standar global perusahaan dengan tuntutan masyarakat adat. “Dalam proses ini, terjadi kontestasi kepentingan yang tidak seimbang,” ujarnya. Masyarakat adat cenderung kuat di isu hak ulayat dan budaya, sementara perusahaan mendominasi aspek kepatuhan standar global.
Jalan Tengah “Hibrid” dan Tantangan Kemandirian
Temuan menarik lainnya adalah soal efektivitas program. Yosef menyimpulkan bahwa program yang terlalu berkiblat ke standar global memang rapi secara administrasi, namun kurang menguatkan institusi lokal. Sebaliknya, program yang terlalu lokal bisa meredam konflik sesaat, namun lemah dalam keberlanjutan jangka panjang.
Solusinya? Pendekatan hibrid.
“Program CSR dengan pendekatan hibrid yang menggabungkan standar global dan kebutuhan lokal dinilai memiliki potensi keberlanjutan paling baik,” tegas Yosef.
Namun, ia memberi catatan kritis. Keberhasilan CSR BP Tangguh dinilai masih bersifat parsial atau setengah jalan. Capaian sosial memang menguat, tetapi kemandirian masyarakat dan strategi keluar (exit strategy) perusahaan belum sepenuhnya kokoh.
Yosef menekankan, pendekatan hibrid harus disertai rencana transisi yang jelas. “Agar tidak menimbulkan ketergantungan struktural masyarakat terhadap perusahaan,” pungkasnya. Riset ini menjadi alarm penting bahwa keberhasilan CSR sejati adalah ketika modal sosial masyarakat berhasil dikonversi menjadi kemandirian institusional yang berkelanjutan.