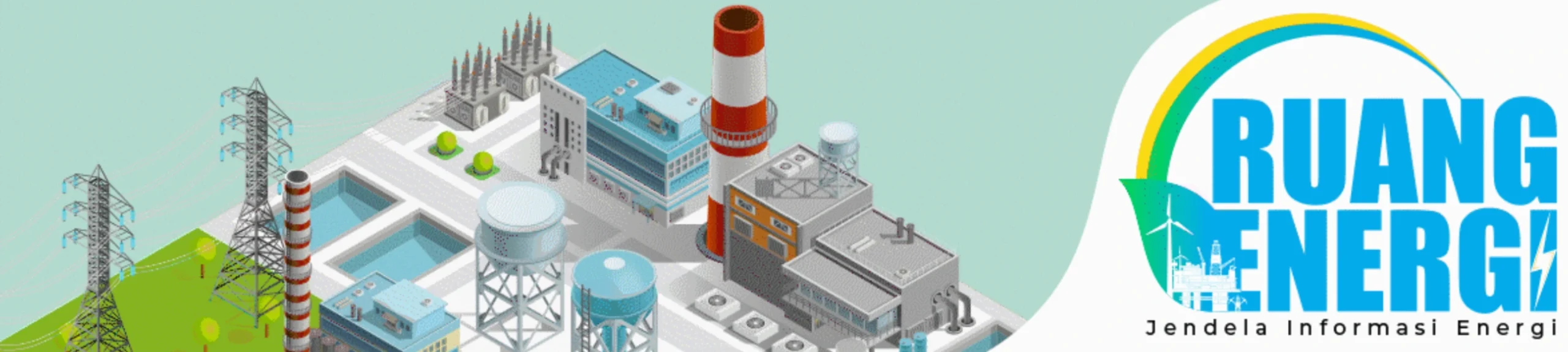Jakarta, ruangenergi – Harga minyak dunia sepanjang 2021 menunjukkan tren meningkat, meski sedikit turun dalam 3 minggu terkahir karena merebaknya virus Omicron. Harga minyak dunia berubah dari US$ 50 per barel (6/1/2021), mencapai level tertinggi US$ 85 (26/10/2021) dan turun ke US$ 73 (20/12/2021). Secara rerata harga minyak mentah naik sekitar 43%. Hal yang sama terjadi untuk gas alam yang naik dari sekitar US$ 2,7 per MMBTU (6/1/2021), level tertinggi US$ 5,8 (4/10/2021) dan US$ 3,8 (20/12/2021). Secara rerata selama 2021, harga gas naik sekitar 37%.
Naiknya harga minyak dunia pasti membuat harga dasar (perolehan) BBM dan gas dalam negeri juga naik. Namun kenaikan harga perolehan ini tidak selalu diiringi kenaikan harga eceran BBM. Hal ini terjadi karena adanya subsidi (BBM tertentu) dan kompensasi (BBM penugasan) dari APBN. Untuk BBM jenis umum, dampak kenaikan minyak dunia bisa langsung dirasakan konsumen yang harus membayar harga eceran BBM yang juga ikut naik. Rujukan aturan tentang harga berbagai jenis BBM antara lain Perpres No.191/2014, Perpres 43/2018 dan sejumlah Peraturan/Keputusan Menteri ESDM.
Namun, meskipun aturan main sudah tersedia, ternyata praktik di lapangan bisa berbeda. Misalnya, untuk BBM jenis umum, badan usaha boleh menaikkan harga BBM sesuai perubahan harga minyak dunia. Syaratnya harus merujuk formula dari Kementrian ESDM dan rencana kenaikan tersebut “diberitahukan” kepada pemerintah. Badan usaha seperti Shell dengan mudah dapat melakukan penaikan harga eceran BBM Shell Super (RON 92) dan Shell V-power (RON 95), seperti yang terjadi sejak April 2021.
Ternyata meskipun masuk kategori jenis BBM Umum, Pertamina tidak bisa langsung menaikkan harga produknya seperti Pertalite (RON 90) dan Pertamax (RON 92). Pertamina tidak mendapat persetujuan pemerintah sebagaimana Shell. Perbedaan perlakuan ini bisa saja menjadi beban (kerugian) Pertamina, yang minimal harus menanggung cost of money sebelum kelak memperoleh kompensasi dari APBN. Jika kompensasi dibayarkan, maka pemerintah telah menggunakan uang negara mensubsidi konsumen BBM yang umumnya adalah golongan masyarakat mampu. Kompensasi ini jelas merupakan subsidi yang tak tepat sasaran.
Hal yang sama terjadi untuk produk LPG yang dijual Patra Niaga (subholding Pertamina) yang terbagi dalam jenis LPG 3kg bersubsidi, serta LPG 5,5kg dan LPG 12kg non-subsidi. Harga beli LPG (Contract Price Aramco, CPA) yang mayoritas diimpor dari Saudi Arabia, dalam setahun telah naik sekitar 57%, yakni dari US$ 538 per metrik ton (MT) menjadi US$ 847 per MT. Untuk produk LPG 3kg, kenaikan harga CPA tidak dirasakan oleh konsumen, karena harga ecerannya selalu disubsidi APBN.
Namun untuk LPG non-subsidi, meski Pertamina mempunyai “wewenang” menaikkan harga, karena belum mendapat persetujuan pemerintah, maka harga LPG non-subsidi tidak dapat dinaikkan.
Karena tidak mendapatkan kompensasi APBN sebagaimana BBM Umum, maka selisih harga beli CPA dengan harga eceran LPG non-subsidi menjadi tanggungan Pertamina. Berdasarkan perhitungan sederhana, kerugian Patra Niaga dari bisnis LPG non subsidi ini sekitar Rp 291 miliar per bulan, dan bisa lebih dari Rp 3 triliun per tahun.
Kenaikan harga BBM atau LPG pasti akan menambah beban belanja rakyat, sehingga wajar jika kita dan konsumen menolak. Kenaikan harga dapat dicegah jika seluruh dampak kenaikan harga minyak dan gas dunia ditanggung APBN. Namun karena keterbatasan keuangan negara, maka wajar pula jika subsidi hanya diberikan pada golongn tidak mampu. Selebihnya, golongan yang berpunya harus siap menerima kenaikan harga BBM dan LPG, sebab mayoritas produk energi gas tersebut diimpor.
Hal utama yang selama ini bermasalah adalah ketidakmampuan penyelenggara negara menyiapkan sistem subsidi tepat sasaran. Dampaknya antara lain meningkatnya beban subsidi APBN, tingginya penikmat subsidi kalangan mampu (lebih dari 70%), meningkatnya jurang kaya-miskin (Gini Ratio: 0,38), tidak berkembangnya EBT, rendahnya ketahanan energi dan terganggunya bisnis dan survival BUMN. BUMN energi kita rawan gagal bayar, bangkrut atau sebagian bisnisnya berlaih ke swasta yang berujung pada naiknya harga atau tarif.
Hal lain adalah penegakan aturan yang bermasalah. Dalam kasus BBM Umum, dengan merujuk kepada aturan yang sama, SPBU asing leluasa menaikkan harga setelah “memberi tahu” pemerintah. Namun hal ini tidak berlaku bagi Pertamina untuk produk Pertalite dan Pertamax, serta juga untuk LPG non-subsidi. Walau sudah memberi tahu dan meminta persetujuan pemerintah, ternyata persetujuan kenaikan harga tidak otomatis diperoleh. Sehingga bisnis BUMN ini terganggu dan survivalnya terancam.
Kita mencatat Dirjen Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengaku telah membahas rencana penyesuaian tarif listrik dengan Banggar DPR. Prinsipnya tarif listrik yang terbagi dua golongan (pelanggan bersubsidi dan non-subsidi), kemungkinan akan naik. Hal ini tak lepas dari variables penentu biaya pokok penyediaan listrik yang naik dan tarif dasar listrik yang berlaku saat ini dianggap tidak relevan karena ditetapkan 2017, sehingga perlu disesuaikan.
Tarif LPG juga sudah berlaku sejak 2017. Kurs US$/Rp telah naik signifikan dan harga beli LPG (CPA) telah naik 57%. Ternyata pemerintah belum berperan sebagaimana pada sektor listrik. Dirjen Kelistrikan sudah terbuka tentang adanya pembahasanan penyesuaian tarif listrik dengan Banggar DPR. Namun untuk LPG non-subsidi, kita belum melihat apa dan bagaimana sikap Ditjen Migas. Padahal Pertamina secara resmi telah mengusulkan penyesuaian tarif.
Masalah subsidi tidak tepat sasaran dan inkonsistensi penegakan aturan ternyata selalu terkait dengan masalah lain yang cukup menentukan, yaitu kepentingan politik pencitraan guna meraih kekusasaan. Sepanjang aspek politik masih dominan, maka kebijakan pemerintah menetapkan tarif listrik, BBM dan LPG tidak akan objketif dan berkeadilan. Sehingga pelayanan publik tidak optimal dan eksistensi BUMN pun terancam. Situasi bisa semakin parah jika rencana privatisasi via holdingisasi terus berlanjut.
Guna menjamin pelayanan energi berkelanjutan, sepanjang berkeadilan dan sesuai prinsip GCG, maka penyesuaian harga LPG non-subsidi tampaknya bisa diterima publik. Rakyat sangat berkepentingan dengan ketahanan energi yang meningkat dimana salah satu aktornya adalah BUMN yang dikelola sesuai konstitusi. Karena itu ke depan, penyelenggara negara antara lain perlu membuat kebijakan komprehensif berupa subsidi tepat sasaran, bebas politik pencitraan, menjunjung prinsip GCG, dan menjamin pengelolaan oleh BUMN, serta membuat peraturan sesuai konstitusi dan konsisten diterapkan.(Marwan Batubara, IRESS)