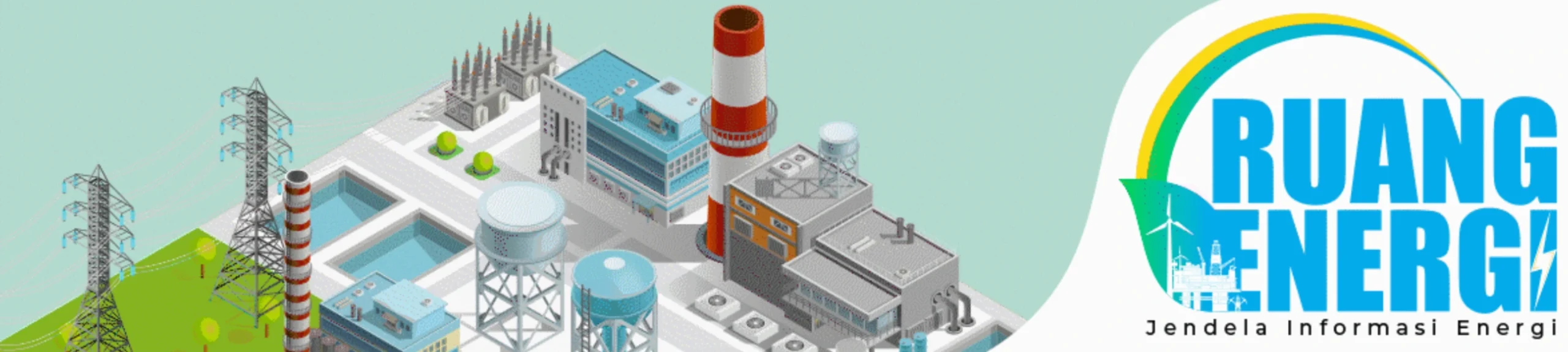Jakarta, ruangenergi.com-Setiap kali nama Natuna atau Ambalat muncul dalam ruang publik, reaksi yang muncul hampir selalu sama: kegelisahan tentang kedaulatan. Seolah-olah setiap pembicaraan mengenai kerja sama di wilayah tersebut identik dengan pelemahan posisi Indonesia.
Cara pandang semacam ini dapat dimengerti secara emosional, tetapi bermasalah secara strategis. Ia menutup ruang diskusi rasional dan berisiko membuat Indonesia kehilangan peluang ekonomi dan geopolitik yang justru lahir dari pemahaman hukum laut internasional.
Yang jarang disadari adalah bahwa Indonesia sebenarnya termasuk negara yang relatif berhasil dalam menyelesaikan delimitasi batas maritimnya. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah menuntaskan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif dengan sejumlah negara tetangga, termasuk Vietnam dan Malaysia. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dicapai melalui pendekatan damai, konsisten dengan UNCLOS 1982, dan diakui secara internasional.
Artinya, isu Natuna dan Ambalat bukanlah cerminan kegagalan Indonesia, melainkan sisa persoalan yang bersifat sangat spesifik.
Di titik inilah penting untuk meluruskan satu kesalahpahaman mendasar. Wilayah yang sering diperdebatkan di Laut Natuna Utara versi Indonesia maupun di Ambalat, Laut Sulawesi, berada di luar laut teritorial Indonesia. Dengan kata lain, wilayah tersebut bukan wilayah kedaulatan, melainkan wilayah hak berdaulat. Perbedaan ini krusial, karena laut teritorial bersifat absolut dan tidak dapat dikompromikan, sementara wilayah hak berdaulat justru diatur oleh hukum internasional untuk memungkinkan pengelolaan yang fleksibel dan pragmatis.
Kesalahan persepsi sering terjadi karena berbagai konteks dicampuradukkan.
Di satu sisi, Indonesia telah menyepakati delimitasi ZEE dengan Vietnam dan Malaysia secara final. Di sisi lain, Indonesia menghadapi klaim nine-dash line Tiongkok yang tidak diakui UNCLOS dan ditolak oleh banyak negara. Kedua situasi ini tidak bisa disamakan. Ketegasan Indonesia terhadap klaim yang tidak memiliki dasar hukum internasional tidak berarti menutup seluruh ruang pengelolaan kepentingan di wilayah hak berdaulat yang sensitif secara geopolitik.
Presiden Prabowo Subianto sesungguhnya memahami perbedaan ini secara jernih. Dalam pertemuannya dengan Presiden Xi Jinping, Presiden menegaskan pentingnya dialog dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Dalam konteks Ambalat dan Laut Sulawesi, pendekatan serupa ditempuh melalui pembicaraan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Pesan utamanya jelas: Indonesia tidak mengendurkan prinsip hukum, tetapi memilih cara yang lebih strategis untuk mengelola realitas geopolitik.
Namun, arah politik di tingkat kepala negara membutuhkan tindak lanjut kelembagaan. Tanpa instrumen kebijakan yang konkret, dialog berisiko berhenti sebagai simbol diplomasi. Di sinilah gagasan Joint Energy Border Authority (JEBA) menjadi relevan, asalkan dipahami secara proporsional dan presisi.
JEBA bukanlah mekanisme untuk mengelola seluruh Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan bukan pula upaya membuka kembali batas-batas yang telah disepakati. JEBA adalah instrumen selektif untuk wilayah tumpang tindih tertentu yang berada di luar laut teritorial, dirancang untuk mengelola potensi energi tanpa prejudis terhadap posisi hukum masing-masing negara. Prinsip ini sejalan dengan praktik internasional dan telah terbukti mampu menciptakan stabilitas jangka panjang.
Dalam konteks Laut Natuna Utara, pendekatan ini memiliki dimensi geostrategis yang kuat. Kawasan ini berada di tengah interaksi kekuatan besar dan jalur perdagangan energi global. Di saat yang sama, potensi migasnya menghadapi tantangan teknis berat, termasuk kandungan CO₂ yang sangat tinggi. Pengembangan wilayah ini membutuhkan kepastian jangka panjang, teknologi kelas dunia, dan stabilitas geopolitik—sesuatu yang sulit dicapai tanpa kerangka kerja sama yang kredibel.
Ambalat menghadirkan dinamika serupa dalam skala bilateral. Selama puluhan tahun, wilayah ini lebih sering menjadi simbol sengketa daripada sumber nilai ekonomi. Padahal, secara hukum internasional, Ambalat berada di ruang hak berdaulat yang memang belum terdelimitasi secara final. Mengelolanya melalui otoritas bersama justru dapat mengakhiri kebuntuan dan mengubah potensi konflik menjadi kepentingan bersama.
Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah konteks transisi energi dan investasi global. Meskipun dunia bergerak menuju energi yang lebih bersih, proyek migas frontier tetap memainkan peran strategis dalam menjamin ketahanan energi dan stabilitas pasokan.
Investor global semakin sensitif terhadap risiko geopolitik dan tata kelola. Negara yang mampu menunjukkan kepastian hukum dan kedewasaan kebijakan akan lebih dipercaya dalam menarik modal dan teknologi.
Pengelolaan energi di wilayah perbatasan tidak pernah bersifat teknis semata. Ia selalu berada dalam konteks geostrategi energi global, di mana energi menjadi instrumen ekonomi sekaligus geopolitik. Cara Indonesia mengelola Natuna dan Ambalat akan dibaca dunia sebagai indikator kapasitas Indonesia dalam menavigasi dinamika global—apakah reaktif dan defensif, atau rasional dan berorientasi jangka panjang.
Dalam kerangka ini, JEBA bukanlah pengaburan kedaulatan, melainkan ekspresi kedewasaan kebijakan. Ia menunjukkan bahwa Indonesia memahami dengan tepat di mana kedaulatan harus ditegaskan secara absolut, dan di mana kepentingan nasional justru dilindungi melalui kerja sama yang cerdas. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menjaga haknya, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara maritim besar yang mampu mengubah ruang sensitif menjadi peluang strategis di tengah geopolitik global yang terus bergerak.
Jakarta, Desember 2025
Sampe L. Purba, Doktor Geostrategi Energi, Alumni Universitas Pertahanan RI