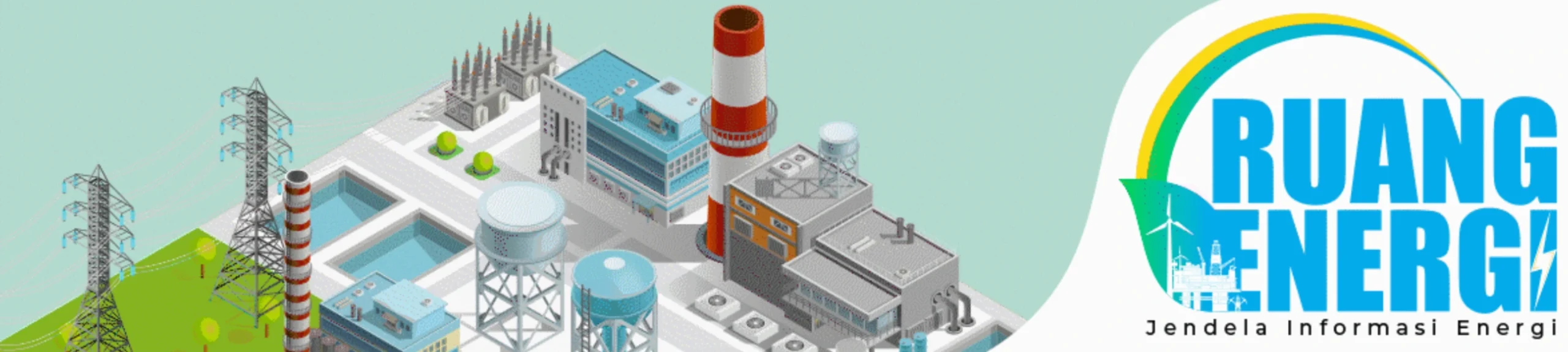Jakarta, ruangenergi.com – Kebijakan Pertamina yang memblokir ratusan ribu nomor polisi kendaraan karena terindikasi menyalahgunakan BBM bersubsidi telah menjadi penanda paling jelas bahwa infrastruktur regulasi kita tidak lagi mampu mengikuti dinamika kebijakan energi di era digital. Tindakan administratif yang dilakukan melalui integrasi sistem Subsidi Tepat dan penggunaan platform My Pertamina sesungguhnya menunjukkan dua wajah dari transformasi tata kelola subsidi.
Satu sisi teknologi menghadirkan kemampuan baru untuk mendeteksi anomali pembelian, mengawasi perilaku konsumen, dan mengurangi kebocoran anggaran. Namun disisi lain, teknologi yang bekerja tanpa landasan hukum yang kokoh dapat menciptakan persoalan baru seperti kesalahan blokir, eksklusi kelompok rentan, hingga munculnya bias algoritmik yang tidak mudah diawasi publik.
Fenomena pemblokiran massal ini telah mengkonfirmasi satu hal, bahwa tata kelola subsidi BBM tidak cukup hanya diperkuat dari sisi teknis, tetapi memerlukan pembaruan hukum yang benar-benar relevan dengan ekosistem data, digitalisasi, dan kebutuhan transparansi publik saat ini.
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada dasarnya tidak dirancang untuk menghadapi realitas baru penyaluran subsidi berbasis data dan algoritma. Regulasi tersebut berangkat dari asumsi bahwa pendistribusian BBM dapat dikendalikan melalui penetapan kuota, harga, dan skema penugasan, tanpa kebutuhan verifikasi digital atau mekanisme keberatan administratif yang cepat.
Padahal, dalam konteks kebijakan subsidi BBM hari ini, aspek teknis penyaluran tidak dapat dipisahkan dari aspek tata kelola data dan hak warga negara. Ketika pemerintah mendorong implementasi QR Code, registrasi NIK-STNK, dan verifikasi digital untuk mendapatkan BBM bersubsidi, muncul kebutuhan mendesak untuk memberi kerangka hukum yang memperjelas batas kewenangan pelaksana seperti Pertamina, menetapkan standar retensi dan penggunaan data pribadi, menyusun mekanisme banding bagi warga yang merasa salah blokir, serta memastikan pembagian peran yang tegas antara regulator dan operator lapangan.
Tanpa revisi regulasi, penguatan digitalisasi justru membuka potensi ketidakpastian hukum. Warga yang terblokir tidak memiliki prosedur remedial yang jelas, SPBU menghadapi tekanan operasional ketika berhadapan dengan konsumen yang merasa berhak dan Pertamina menanggung risiko sosial serta hukum yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pembaruan Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bukan sekadar pembaruan norma, tetapi merupakan infrastruktur kebijakan yang menentukan legitimasi seluruh proses digitalisasi subsidi. Tanpa payung hukum yang kuat, upaya digital seperti My Pertamina akan terus berjalan di atas pijakan yang rapuh.
Beban Pertamina
Dalam konteks implementasi kebijakan subsidi BBM, Pertamina berada dalam posisi dilematis. Sebagai BUMN energi, perusahaan ini diberi mandat untuk menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran, sekaligus menjaga stabilitas pasokan nasional. Namun pada saat yang sama, Pertamina dipaksa mengemban tanggung jawab yang sejatinya merupakan otoritas negara yakni menjaga ketepatan penerima subsidi, memastikan integritas data, hingga menghadapi tuntutan sosial dari warga yang merasa dirugikan.
Ketika Pertamina menggunakan algoritma untuk mendeteksi pola pembelian yang mencurigakan, kemudian berani mengambil langkah pemblokiran terhadap nomor polisi yang diduga menyalahgunakan subsidi, perusahaan sesungguhnya menempuh kebijakan penegakan yang sulit dan syarat risiko. Tindakan ini mungkin efektif secara teknis dalam jangka pendek, namun sekaligus menempatkan Pertamina di garis depan konflik politik, sosial, dan hukum yang melekat pada kebijakan subsidi.
Beban yang ditanggung Pertamina tidak semata-mata bersifat teknis. Ada beban fiskal akibat skema subsidi yang terus membengkak, beban operasional akibat kewajiban pengawasan harian yang kompleks, beban reputasi ketika publik menilai perusahaan terlalu keras atau tidak adil, serta beban regulatif ketika masih banyak celah hukum dalam penegakan kepatuhan di lapangan.
Selain itu, implementasi teknologi Subsidi Tepat memerlukan investasi besar mulai dari infrastruktur sistem, server, integrasi data, pelatihan petugas SPBU, hingga layanan pelanggan untuk menangani protes atau sanggahan dari masyarakat. Bahkan, salah satu beban terbesar muncul ketika terjadi “false-positive” blokir yang salah sasaran akibat ketidaksinkronan data atau anomali yang dibaca algoritma sebagai indikasi fraud. Dalam kasus seperti itu, Pertamina harus menjawab tuntutan publik, padahal mereka tidak memiliki dasar hukum yang secara eksplisit mengatur penyelesaian sengketa administratif.
Oleh karena itu, langkah preventif seperti pemblokiran nomor polisi harus disertai dengan prosedur banding yang cepat, terbuka, dan terukur. Mekanisme audit independen juga menjadi prasyarat agar tindakan Pertamina dapat diuji secara objektif dan tidak menimbulkan kecurigaan publik.
Pertamina harus melaksanakan mandat negara, namun negara perlu kembali mengambil perannya dalam menyediakan pedoman hukum, pengawasan, dan mekanisme perlindungan sosial. Tanpa redistribusi tanggung jawab tersebut, Pertamina akan terus berada dalam posisi serba salah yakni dihukum jika terlalu longgar, disalahkan jika terlalu ketat.
Inisiatif MyPertamina
Program Subsidi Tepat melalui My Pertamina merupakan inovasi kebijakan yang secara teknis mampu mengatasi kelemahan skema subsidi berbasis konsumsi. Dengan menghubungkan transaksi pembelian dengan identitas kendaraan dan pemilik melalui QR Code, system ini membuka peluang untuk mengendalikan distribusi BBM bersubsidi lebih presisi dan lebih terverifikasi.
Anomali frekuensi pembelian, lonjakan volume, dan pola transaksi yang tidak wajar dapat dideteksi secara real-time, sehingga kebocoran yang sebelumnya sulit dipantau kini dapat ditekan. Ini adalah lompatan besar dibandingkan model sebelumnya yang mengandalkan pendekatan universal tanpa verifikasi identitas.
Namun digitalisasi penyaluran subsidi bukanlah sekadar implementasi teknologi. Digitalisasi menciptakan ketergantungan baru terhadap integrasi data lintas-institusi, Dukcapil harus menyediakan data kependudukan yang akurat, Korlantas harus memastikan database STNK mutakhir, Pertamina harus menjaga integritas sistem, dan pemerintah harus menetapkan aturan pertukaran data yang legal dan dapat diaudit. Tanpa ekosistem tata kelola data yang solid, satu titik kegagalan dapat mengakibatkan ribuan warga terblokir atau kehilangan akses subsidi, bukan karena pelanggaran, tetapi karena ketidaksinkronan sistem.
Kebutuhan akan prosedur alternatif juga menjadi sangat penting. Tidak semua masyarakat memiliki akses digital yang memadai. Pekerja sektor informal, sopir angkot, pelaku usaha kecil, atau warga di daerah terpencil sering kali terbatas peralatan digital maupun akses internetnya. Jika skema digital diterapkan tanpa jalur manual yang layak, digitalisasi akan memperbesar eksklusi sosial, bukan memperbaiki ketepatan sasaran. Inilah tantangan paling fundamental: bagaimana memastikan bahwa teknologi memperluas akses, bukan membatasi.
Dari perspektif fiskal, pergeseran ke subsidi tertarget membuka peluang signifikan bagi negara untuk menghemat anggaran. Anggaran yang terbebas dapat dialihkan untuk pembangunan energi bersih, infrastruktur desa, atau program sosial yang lebih produktif. Namun penghematan ini hanya valid jika sistem bekerja dengan akurasi tinggi. Jika false-positive tinggi, negara justru menciptakan beban sosial baru yang berbiaya politik dan ekonomi lebih besar. Karena itu, audit independen wajib dilakukan untuk memverifikasi klaim penghematan dan mengukur tingkat akurasi sistem sebelum kebijakan diperluas.
Rekomendasi Kebijakan
Pertama, revisi Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak harus menjadi prioritas. Regulasi tersebut perlu diperluas untuk memasukkan ketentuan digitalisasi subsidi, seperti kewenangan verifikasi, batasan penggunaan data pribadi, durasi penyimpanan data, serta prosedur penanganan keberatan.
Kedua, pemerintah harus menetapkan standar prosedur banding cepat idealnya 24–72 jam disertai desk layanan di SPBU dan kantor pemerintah daerah untuk menangani kasus salah blokir secara cepat dan manusiawi.
Ketiga, negara harus mengambil kembali peran fiskal dan sosialnya. Jika subsidi dibuat lebih tertarget, maka konsekuensinya adalah menyediakan mekanisme kompensasi bagi kelompok rentan yang terdampak selama masa transisi. Keempat, audit independen berkala harus menjadi kewajiban agar setiap klaim penghematan dan efektivitas sistem dapat diuji secara objektif serta menjadi dasar penyesuaian kebijakan.
Reformasi subsidi BBM di era digital bukanlah urusan teknis semata, melainkan sebuah persimpangan antara hukum, teknologi, etika publik, kapasitas institusional, dan keadilan sosial. Pertamina telah mengambil langkah berat dengan memblokir nomor-nomor polisi yang dianggap menyalahgunakan subsidi, namun langkah ini hanya akan memiliki legitimasi jika negara hadir untuk menyediakan payung hukum, mekanisme perlindungan warga, dan sistem pengawasan yang kredibel.
My Pertamina membawa peluang besar menuju penargetan subsidi yang lebih tepat dan efisien, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi algoritma, perlindungan data, penyelesaian sengketa administratif yang adil, dan audit publik yang berkelanjutan. Jika seluruh aspek tersebut diperkuat, maka penghematan fiskal bukan hanya akan menjadi angka di kertas, tetapi akan menjadi ruang fiskal baru yang dapat digunakan untuk membangun masa depan energi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi Indonesia.
Penulis:
Rifqi Nuril Huda, S.H., M.H., CLA., CCD.
Alumni Magister Hukum Sumber Daya Alam Universitas Indonesia. Direktur Eksekutif Institute of Energy and Development Studies (IEDS) dan Ketua Umum Akar Desa Indonesia