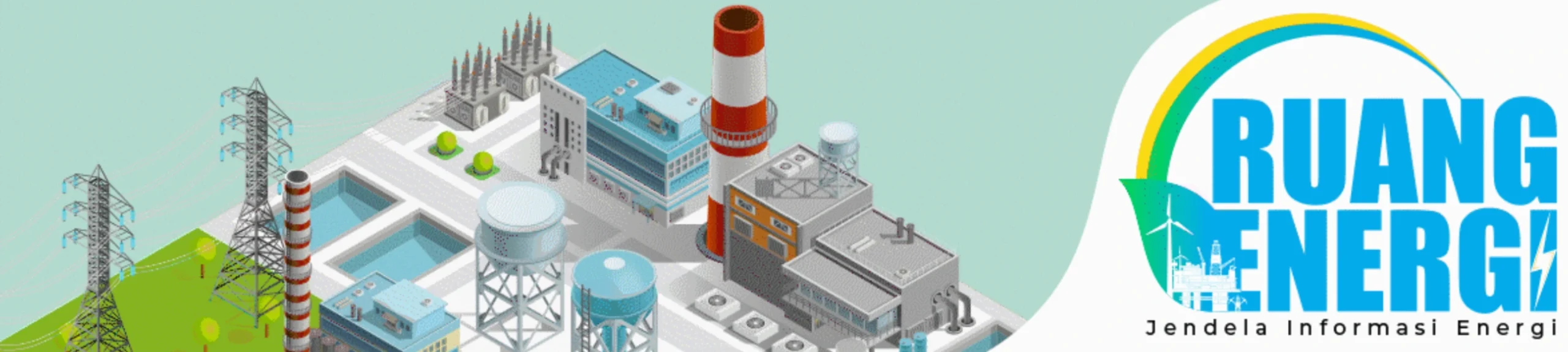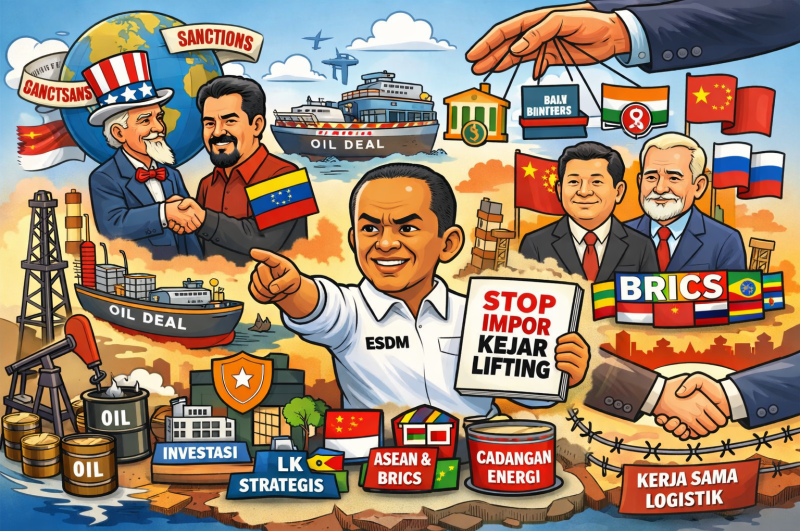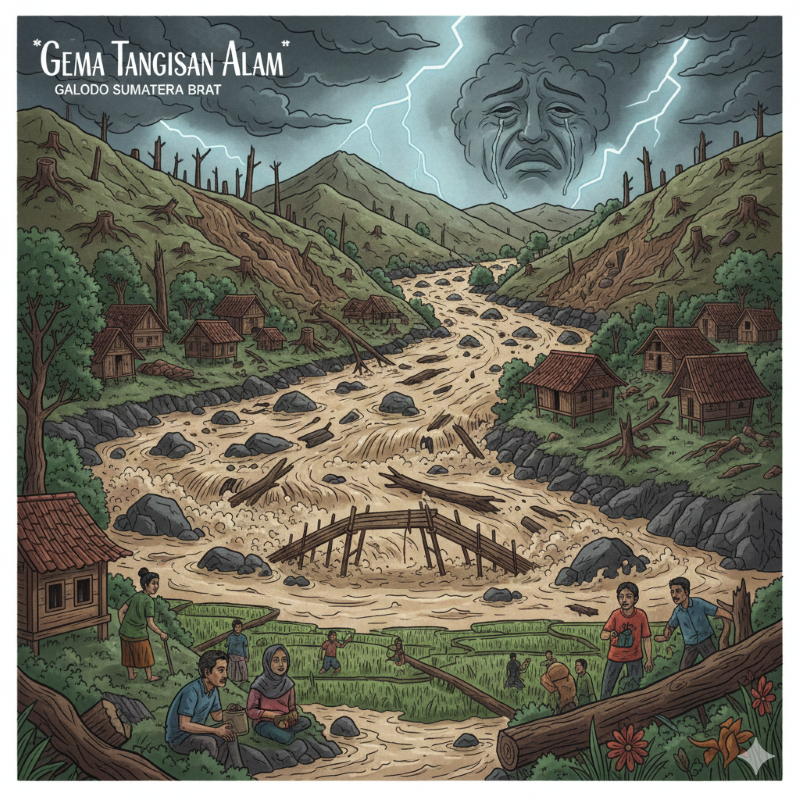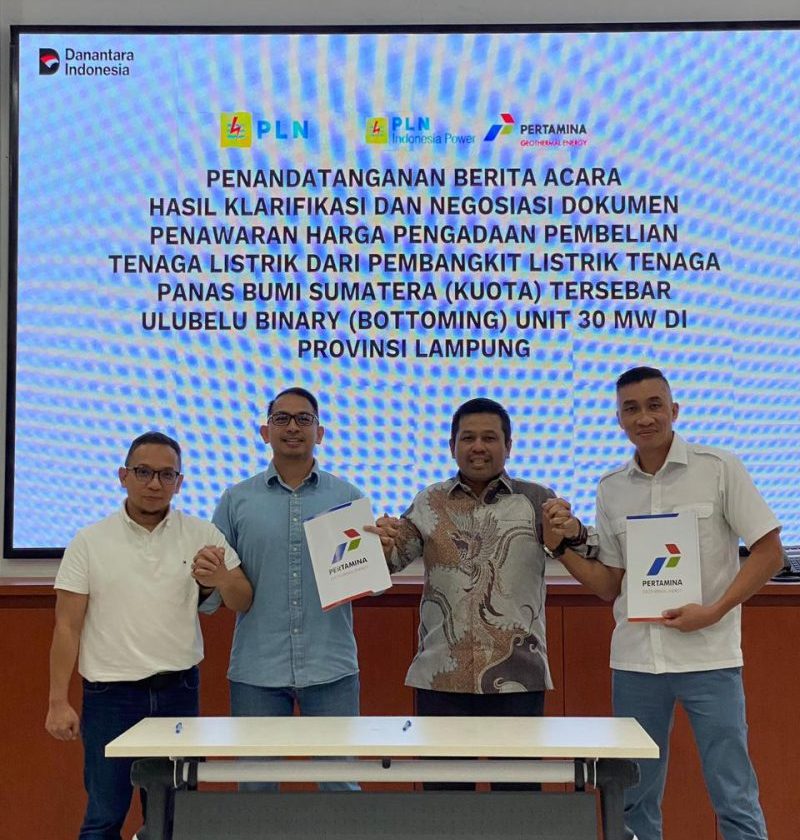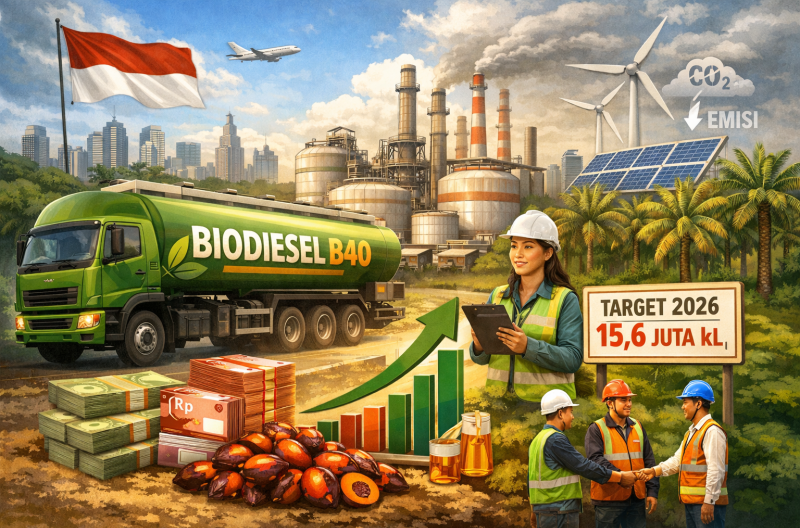Jakarta, Ruangenergi.com – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, menyatakan, dalam hal penurunan emisi gas karbon sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 16 tahun 2016 Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.
“Akhirnya pemerintah langsung menurunkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 61 tahun 2011 terkait dengan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK),” kata Mamit dalam webinar yang bertajuk “Upaya KKKS Mengurangi Emisi Karbon” yang diselenggarakan oleh Ruang Energi melalui platform Zoom dan Channel YouTube Ruang Energi, (17/06).
Di mana dalam Pasal 2 ayat 2, Perpres 61/2011 menjelaskan bahwa “Kegiatan RAN-GRK meliputi : Pertanian, Kehutanan dan lahan gambut, Energi dan Transportasi, Industri, Pengelolaan Limbah, Kegiatan Pendukung lainnya”.
Sementara, dalam Pasal 3 ayat 2, menyatalan bahwa “RAN-GRK merupakan pedoman bagi “ Kementerian/Lembaga dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK dan Pemerintah daerah dalam penyusunan RAD-GRK”.
Pada awalnya pemerintah dalam pertemuan G-20 di Pittsburg telah sepakat untuk melakukan penurunan emisi GRK sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (bussines as usual /BAU).
Akan tetapi, pertemuan G-20 tersebut diratifikasi menjadi 29% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada 2030 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi.
“Target kita besar sekali untuk mengurangi emisi GRK, di mana untuk sektor energi sendiri mencapai 314 juta ton CO2 dengan kemampuan sendiri dan sebesar 392 juta ton CO2 dengan bantuan internasional pada 2030.
“ini adalah suatu PR yang sangat besar, terlebih lagi dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) kita memilik target penggunaan EBT sebesar 23% di 2025, dan butuh effort yang cukup besar agar target tersebut dapat tercapai,”
Lebih lanjut, Mamit menjelaskan, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama stakeholder dalam mengurangi emisi GRK yaitu, pemanfaatan listrik yang bersumber dari EBT; penerapan efisiensi energi; penggunaan bahan bakar nabati (BBN); carbon capture, utilization and storage (CCUS); transisi energi; serta optimalisasi gas suar.
Terkait transisi energi yang saat ini sedang dilakukan di Indonesia, menurut Mamit butuh waktu, sebab transisi energi ini butuh modal yang tidak sedikit dan butuh pembangunan infrastruktur.
“Buat saya ini cukup berat karena masih ketergantungan dengan energi murah terutama batubara. Saya kira transisi energi harus tetap dilakukan secara bertahap, terlebih lagi kita masih memiliki target-target yang memang harus dicapai seperti 1 juta barel di 2030, pembangunan RDMP (Refinery Development Master Plan) dan GRR (Grass Root Refinery) sedang berjalan,” jelasnya.
Ia mengatakan, transisi energi buka hal yang tidak mungkin untuk dicapai, akan tetapi menjadi suatu keharusan, sehingga transisinya bisa berjalan mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.
“Jangan sampai transisi energi ini justru akan memberatkan masyarakat dengan kenaikan-kenaikan tarif ke depannya,” paparnya.
Mamit mengatakan, pada Mei 2021 lalu, International Energy Agency (IEA) meminta secara global untuk melakukan penghentian pengeboran minyak dan gas sesegera mungkin.
“Saya kira ini menjadi suatu ‘tamparan’ untuk kita, bahkan secara global terkait pernyataan dari IEA. Karena hal ini buat saya industri migas adalah salah satu penyumbang PNBP kita yang sangat besar. Ketika wacana ini disampaikan, ini menjadi suatu pukulan sehingga hal ini membuat investasi kita di sektor migas sedikit terganggu. Buat saya pernyataan dari IEA sangat mendiskreditkan industri hulu migas secara global termasuk Indonesia,” tuturnya.
Menurut Mamit di industri hulu migas emisi yang dihasilkan pada saat pengeboran tidak terlalu signifikan, justru di sektor transportasi kendaraan, genset diesel, test uji sumur flaring, pembukaan lahan lah yang banyak menghasilkan emisi karbon.
“Di tingkatan produksi (migas), saya kira tidak terlalu banyak, hanya genset diesel dan flaring gas. Di mana SKK Migas dan para KKKS telah menyiapkan bagaimana mengoptimaliasi gas flaring tersebut.
Tantangan KKKS Mengurangi Emisi Gas Karbon
Mamit menjelaskan, dari sisi teknis diperlukan biaya untuk membangun kembali infrastruktur hulu migas yang telah terpasang sejak lama (tua). Selanjutkan, perlu ada re-desain terhadap peralatan di hulu migas, serta berada di daerah remote atau konservasi.
Sementara, terkait dengan sisi regulasi, Mamit mengatakan, hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi pemerintah sebab perlu adanya regulasi yang mengatur insentif credit carbon, tanpa adanya insentif ini akan sangat berat sekali.
“Mungkin jika memakai skema cost recovery ini akan menjadi beban negara, tapi jika memakai skema gross split ini akan menjadi tanggungan dari KKKS. Saya kira perlu ada insentif yang menarik untuk KKKS dalam mengurangi emisi gas karbon,” imbuhnya.
“Bisnis as usual tidak cukup, serta kebijakan masih bersifat gimmick. Jangansampai ganti pemimpin ganti kebijakan, dan yang akhirnya justru memberatkan KKKS,” sambung Mamit.
Selanjutnya, terkait aspek sosial yaitu, otonomi daerah, perijinan yang menumpuk, gangguan kemanan dari masyarakat.
“Dengan adanya otonomi daerah ini pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang dibuat, yang pada akhirnya ini akan berjalan lebih lambat lagi.
Lalu, aspek ekonomi yaitu, membutuhkan anggaran lebih, biaya riset dan pengembangan yang tinggi.
“Saya kira ini adalah tantangan yang harus diterima dan dihadapi oleh KKKS dalam rangka mengurangi emisi gas karbon,” tandas Mamit.