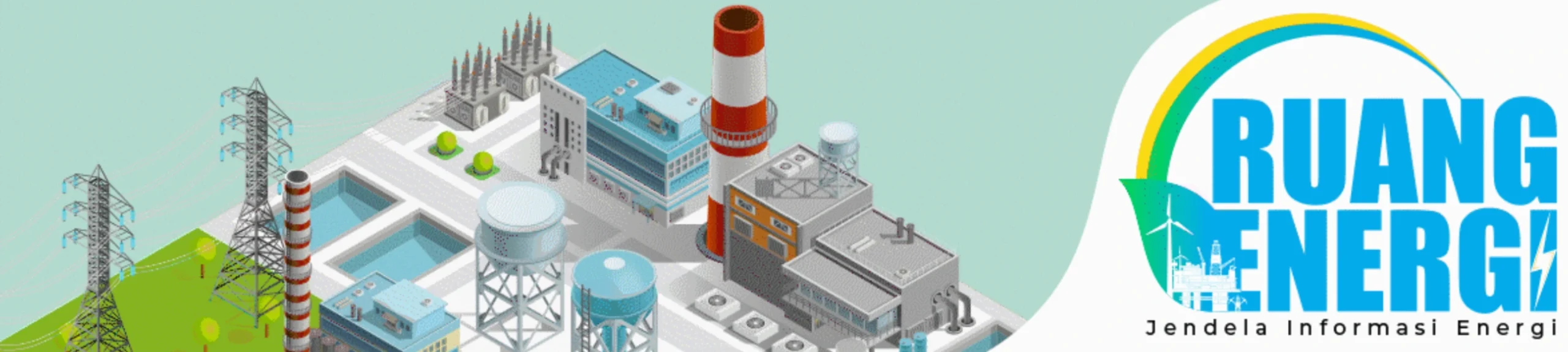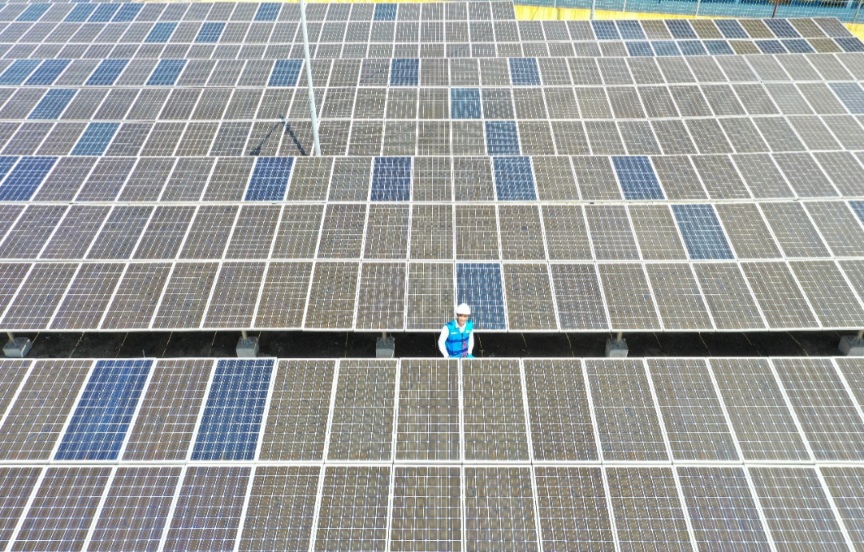Jakarta, Ruangenergi.com – Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia ke-7 periode 1978-1988, Prof. Dr. Soebroto, M.A. mengatakan bahwa Indonesia terus berjuang dalam melakukan transisi energi secara teratur.
“Kita terus menerus melakukan pengkajian, yang penting adalah mendukung usaha pemerintah untuk bisa mengatasi transisi energi secara baik dan teratur,” kata Prof. Soebroto secara virtual dalam gelaran Bimasena Energy Dialogue bertemakan Transformasi Bisnis Sektor Batubara Dalam Rangka Mendukung Transformasi Energi Indonesia, Jumat (19/03).
Ia mengungkapkan, komoditas batubara di Indonesia saat ini sebagian besar masih dimanfaatkan untuk sumber energi dan di ekspor.
Pada tingkat global, pemanfaatannya energi yang bersumber dari fosil (batubara) perlahan mulai ditinggalkan, karena dianggap sebagai kontributor terbesar emisi karbon yang mengakibatkan kenaikan suhu global.
“Indonesia sendiri merupakan dan salah satu satu dari 174 negara yang dalam ratifikasi Paris Agreement, sehingga memiliki kewajiban untuk turut menjaga laju pertumbuhan suhu rata-rata bumi dibawah 2 derajat Celcius hingga 1,5 derajat Celsius,” jelasnya.
Menarik untuk dikutip, pidato Presiden Joko Widodo dalam Conference of Parties (COP) ke-21 di Paris pada November 2015, yang menyatakan bahwa Paris Agreement harus mencerminkan keseimbangan, keadilan serta sesuai dengan prioritas dan kemampuan nasional. Pula mengikat, jangka panjang, ambisius, namun tidak menghambat pembangunan negara berkembang.
Untuk menjaga keseimbangan antara komitmen global dan pemanfaatan secara optimal penggunaan batubara di Indonesia, diperlukan suatu strategi transformasi bisnis yang tepat disesuai dengan kondisi yang rencana pembangunan Indonesia yang masih membutuhkan sumber energi murah dalam jangka panjang.
“Indonesia sanggup menurunkan emisi sebesar 29% pada tahun 2030. Bahkan, sampai 41% jika mendapatkan bantuan internasional. Pada masanya global akan ada transisi ke sumber energi terbarukan. Untuk itu, para pelaku usaha pertambangan batubara harus bisa mengambil peluang dalam proses transisi energi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan inovasi,” bebernya.

Menurutnya, teknologi ultra super critical yang tersedia pada saat ini untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ramah lingkungan, membutuhkan skala proyek diatas 600 Megawatt (MW), guna mendukung keekonomiannya.
“Sehingga ini kurang cocok bagi negara kepulauan seperti Indonesia, padahal teknologi tersebut menjadi persyaratan dalam pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi fosil. Atas hal itu, sumber pendanaan menjadi semakin terbatas, dengan teknologi dan inovasi, seharusnya semua dapat menjadi termanfaatkan, tidak ada lagi limbah sumber polusi,” paparnya.
Disinilah pentingnya peranan research and development dari sisi keterjangkauan teknologi.
Investasi dan risiko sangat besar, pelaku usaha sebagai frontliner perlu sehat secara keuangan agar dapat sustainable, sehingga ekspor komoditas batubara masih menjadi preferensi di sudut pandang para pengusaha untuk memanfaatkan momentum demand yang saat ini masih tinggi.
Sisi lain, sampai saat ini target 23% Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional pada 2025 masih jauh diatas capaian.
“Tercatat pada tahun 2020 capaian EBT sekitar 11,5%. Timbul pertanyaan bagaimana transformasi bisnis yang tepat ?, sejauhmana komoditas batubara sebagai komoditas ekspor akan terus berlanjut ?, lalu bagaimana meningkatkan keekonomian industri hilir berbasis batubara ?, insentif dan fasilitas apa yang dibutuhkan para pelaku usaha untuk meningkatkan keekonomian suatu proyek ?, bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha seperti proper yang baik, kuota DMO yang terpenuhi, kepatuhan pajak dan lain-lain dapat memberikan suatu reward atau insentif bagi pelaku usaha?,” tukasnya.